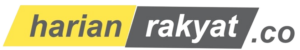Reformasi 1998, 27 tahun silam, seyogianya menjadi momentum pembebasan sejati dari belenggu Orde Baru. Namun, narasi yang terus-menerus mencoba mengkultuskan Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan” atau “pahlawan” adalah bentuk amnesia sejarah kolektif yang berbahaya. Pandangan ini bukan sekadar sentimentalitas emosional, melainkan kritik tajam terhadap struktur kekuasaan dan eksploitasi terhadap Rakyat yang dilegitimasi di bawah rezim otoriter tersebut.
Pembangunan Semu dan Akumulasi Kapitalis Brutal
“Pembangunan” ala Orde Baru Soeharto bukanlah pembangunan yang berpihak pada rakyat pekerja, melainkan akumulasi kapitalis primitif yang brutal (Luxemburg, 1913/2003). Proyekproyek infrastruktur masif dan pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan sejatinya adalah alat untuk memfasilitasi ekspansi modal, baik domestik maupun asing, dengan mengorbankan hakhak buruh dan petani. Data menunjukkan, selama Orde Baru, kesenjangan ekonomi justru melebar. Indeks Gini, meski fluktuatif, tetap menunjukkan bahwa kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir elite yang terafiliasi dengan rezim (World Bank Data). Kebijakan pembangunan berbasis utang luar negeri yang jor-joran ($13,5 miliar pada awal 1990-an) bukan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan untuk memperkaya para komprador dan birokrat kapitalis yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto.
Tanah-tanah rakyat dirampas atas nama pembangunan, upah buruh ditekan melalui kebijakan upah minimum yang tidak realistis, dan organisasi-organisasi buruh independen dibungkam secara represif. Kasus Marsinah hanyalah puncak gunung es dari praktik eksploitasi dan penindasan terhadap kelas pekerja yang sistematis. Pembangunan yang “sukses” ini, dalam analisis Marxis, adalah sukses bagi kelas borjuasi birokrat dan konglomerat yang menikmati rente dari konsesi negara dan eksploitasi sumber daya alam.
Represi Negara sebagai Alat Dominasi Kelas
Tidak ada “stabilitas” tanpa penindasan. Narasi “stabilitas keamanan” Orde Baru adalah eufemisme untuk represi negara yang kejam terhadap setiap bentuk perlawanan kelas dan disiden politik. Pembantaian 1965-1966, yang menargetkan anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta jutaan aktivis kiri lainnya, adalah genosida yang dirancang untuk menghancurkan kekuatan politik potensial yang mengancam dominasi kapitalis.
Angka korban yang mencapai 500.000 hingga 1 juta jiwa, bahkan lebih, adalah bukti kebiadaban rezim ini dalam menegakkan tatanan sosial-ekonomi yang diinginkan. Kemudian, sepanjang kekuasaannya, “stabilitas” itu dijaga melalui militerisme represif, dwifungsi ABRI yang mengintervensi setiap lini kehidupan sipil, sensor ketat, pembungkaman oposisi, dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang merajalela. Kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berpihak pada rezim. Ini adalah kediktatoran borjuis yang menghancurkan potensi emansipasi rakyat.
Di bawah Soeharto, militer menjadi instrumen utama dalam menjaga status quo dan menumpas setiap gerakan yang dianggap “mengganggu pembangunan” atau “mengancam stabilitas”. Dari penindasan terhadap petani di Kedung Ombo hingga pembunuhan aktivis buruh, aparat negara digunakan sebagai garda terdepan kepentingan kapital. Aparatus ideologis negara, melalui indoktrinasi P4 (Penataran, Pedoman, Penghayatan, dan Pengalaman Pancasila) dan sensor media, bekerja keras untuk menanamkan loyalitas buta dan melumpuhkan kesadaran kritis masyarakat. Ini adalah manifestasi nyata dari tesis Marxis bahwa negara, dalam masyarakat berkelas, adalah komite yang mengelola urusan bersama seluruh kelas borjuis (Marx & Engels, 1848/2004).
Korupsi sebagai Mekanisme Akumulasi Borjuasi
Korupsi di era Orde Baru bukan sekadar “penyakit” individual, melainkan mekanisme inheren dalam akumulasi kapitalis Soeharto dan kroni-kroninya. Nepotisme, kolusi, dan korupsi (KKN) menjadi sistemik, di mana kekayaan negara diprivatisasi untuk memperkaya keluarga dan lingkaran elite penguasa. Transparansi International (TI) bahkan pernah menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan estimasi kekayaan yang diselewengkan mencapai $15-35 miliar (Transparency International, 2004).
Ini bukan anomali, melainkan ciri khas dari sistem kapitalisme yang bergantung pada hubungan patronase dan ekstraksi rente. Korupsi ini secara langsung memiskinkan rakyat banyak, karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk layanan publik atau investasi produktif justru mengalir ke kantong-kantong pribadi segelintir orang. Mengabaikan aspek korupsi ini saat membahas “pahlawan” Soeharto berarti mengabaikan penderitaan jutaan rakyat akibat penjarahan sistematis.
Mengapa Soeharto Tidak Boleh Jadi Pahlawan
Mengagungkan Soeharto sebagai pahlawan adalah upaya untuk memutarbalikkan sejarah, mengaburkan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan menutupi eksploitasi Rakyat yang terjadi sellama ini. Kepahlawanan sejati terletak pada perjuangan kolektif rakyat pekerja untuk pembebasan dari segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Para korban ’65, aktivis buruh yang dibungkam, petani yang tergusur, dan seluruh rakyat yang hidup dalam ketakutan dan kemiskinan di bawah rezim otoriter adalah pahlawan sejati yang berjuang demi keadilan.
Reformasi 1998, meski belum sempurna dan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah dalam mencapai keadilan sosial, adalah hasil dari perlawanan rakyat terhadap tirani. Mengembalikan citra Soeharto sebagai pahlawan adalah upaya untuk mendelegitimasi perjuangan tersebut dan membuka jalan bagi kemungkinan kembalinya bentuk-bentuk otoritarianisme demi kepentingan kapital.
27 tahun setelah lengser, warisan Orde Baru masih menghantui Indonesia. Oligarki yang dibentuk dan dibesarkan pada masa Soeharto masih berkuasa hingga hari ini, mengontrol politik dan ekonomi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilembagakan pada masa itu telah menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Militerisme, meskipun tidak sekuat dulu, masih memiliki jejak pengaruh yang dalam. Kekerasan negara terhadap rakyat, perampasan tanah, dan pembungkaman kritik adalah residu pahit dari rezim otoriter tersebut.
Oleh karena itu, di usia 27 tahun Reformasi, penting untuk menegaskan kembali: Soeharto bukanlah pahlawan. Ia adalah representasi dari sebuah sistem yang menindas dan mengeksploitasi. Pemahaman sejarah yang kritis dan berpihak pada kelas tertindas adalah langkah fundamental menuju pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Ditulis Oleh Wawan Darmawan – Anggota Komite Politik (Kompol) Kaltim | Juga Anggota Kelompok Belajar Anak Muda